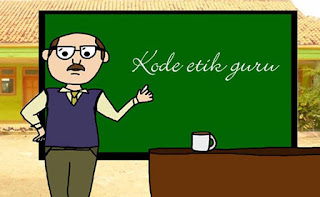Kurikulum 2013 versi 2016 yang berlaku di Indonesia saat ini meminta
guru untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat mempengaruhi siswa untuk
berpikir kritis dan mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order
thinking skills atau HOTS) (Husnawati, dkk., 2019). Kompetensi Inti Pengetahuan
Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa peserta didik diharapkan mampu memahami,
menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Begitupun
juga pada Kompetensi Inti Keterampilan peserta didik diharapkan mampu mengolah,
menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
(Malik, dkk., 2015).
Salah satu tugas yang penting dilakukan oleh guru adalah
mengembangkan instrumen penilaian. Proses pembelajaran yang baik akan tercermin
dari penilaian hasil belajar yang dilakukan dengan menggunakan instrumen
penilaian yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang
telah ditetapkan (Siswoyo & Sunaryo, 2017). Dalam hal ini, pengembangan soal
HOTS sangat diperlukan dalam suatu pembelajaran untuk melatih siswa berpikir
kritis, tak terkecuali juga dalam pembelajaran fisika.
Menurut Efendi (2010), berdasarkan hasil TIMSS diperoleh kesimpulan
sebagai berikut: (1) rata-rata pencapaian fisika siswa Indonesia yang ditinjau
dari aspek kognitif masih rendah; (2) kecenderungan pencapaian fisika siswa
Indonesia selalu menurun pada setiap aspek kognitif. Salah satu faktor yang
menyebabkan kemampuan berpikir siswa masih rendah adalah kurang terlatihnya siswa
Indonesia dalam meyelesaikan tes atau soal yang menuntut adanya analisis,
evaluasi, dan kreativitas. Soal-soal yang mempunyai karakteristik tersebut
adalah soal-soal untuk mengukur HOTS (Dewi & Riandi, 2016).
Peningkatan HOTS merupakan salah satu prioritas dalam pembelajaran
sains dalam sekolah. Pengajaran HOTS dilandasi dua filosofi: harus ada materi
atau pelajaran khusus tentang berfikir dan mengintegrasikan kegiatan berfikir
ke dalam pembelajaran fisika. Dengan demikian, keterampilan berfikir terutama
HOTS perlu dikembangkan dan menjadi bagian dari pelajaran fisika sehari-hari.
Dengan pendekatan ini, keterampilan berfikir dapat dikembangkan dengan cara
membantu siswa dalam memecahkan permasalahan menjadi lebih baik. Oleh sebab
itu, guru harus menyediakan masalah (soal) yang memungkinkan peserta didik
mengunakan HOTS (Pratama & Istiyono, 2015).
High Order Thinking Skills (HOTS) adalah konsep reformasi
pendidikan berdasarkan taksonomi bloom. Idenya adalah bahwa beberapa jenis
pembelajaran memerlukan pengolahan lebih kognitif daripada yang lain, tetapi
juga memiliki manfaat yang lebih umum (Siswoyo & Sunaryo, 2017). Dalam taksonomi Bloom (Anderson &
Krathwohl, 2001) keterampilan analisis, evaluasi dan sintesis merupakan tingkat
berpikir yang lebih tinggi, yang mana memerlukan pembelajaran dan metode
pengajaran yang berbeda daripada sekedar belajar fakta-fakta dan konsep.
Berpikir tingkat tinggi (HOTS) melibatkan keterampilan menilai yang kompleks,
misalnya berpikir kritis dan pemecahan masalah.
Soal HOTS memiliki hubungan yang sangat erat dengan berpikir
kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial
dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga di bidang Pendidikan (Husnawati,
dkk., 2019). Menurut Yee, dkk (2011), berpikir tingkat tinggi dikategorikan
sebagai berpikir yang non algoritmik, bermakna, kompleks, menghasilkan banyak
solusi, sukar, sarat dugaan, tidak pasti, dan memiliki banyak kriteria.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi mendorong seseorang untuk dapat menerapkan
informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk
menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru (Heong, dkk., 2011). Menurut
taksonomi Bloom yang telah direvisi, proses kognitif terbagi menjadi kemampuan
berpikir tingkat rendah meliputi kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan,
sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan menganalisis,
mengevaluasi, dan menciptakan (Anderson & Krathwohl, 2001).
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa melalui
pengembangan soal-soal HOTS diharapkan para pendidik dapat mengukur kemampuan
berpikir tingkat tinggi siswa dengan tepat dan dapat melatih siswa dengan
soal-soal HOTS, sehingga dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia,
khususnya pada kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Daftar
Pustaka
Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. 2001. A Taxonomy of Learning,
Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives. New York: Longman.
Dewi, N. & Riandi, R. 2016. Analisis Kemampuan Berpikir
Kompleks Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Mind Mapping. Jurnal
EduSains, 8 (1), 98-107. Dari http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/edusains/article/view/1805.
Efendi, R. 2010. Kemampuan Fisika Siswa Indonesia dalam TIMSS. Prosiding
Seminar Nasional Fisika 2010. ISBN: 978-979-98010-6-7.
Heong, Y. M., Othman, W.D., Yunos, M. D. J., Kiong, T.T., Hassan,
R., & Mohamad, M. M. 2011. The Level of Marzano Higher Order Thinking
Skills Among Technical Education Students. International Journal of Social
and Humanity, 1 (2), 121-125. Dari https://www.semanticscholar.org/paper/The-Level-of-Marzano-Higher-Order-Thinking-Skills-Heong-Othman/6e5a76e3994e6a23df6c3296dd9d9c940d1198b7?p2df.
Husnawati, A., Hartono., & Masturi. 2019. Pengembangan Soal
Higher Order Thinking Skill (HOTS) Fisika Kelas VIII SMP Materi Gerak Pada
Benda. Unnes Physics Education Journal, 8 (2), 134-140. Dari https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej/article/view/33320.
Malik, A., Ertikanto, C., & Suyatna, A. 2015. Deskripsi
Kebutuhan HOTS Assessment Pada Pembelajaran Fisika dengan Metode Inkuiri
Terbimbing. Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2015, 4, 4.
Dari http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosidingsnf/article/view/5011.
Pratama, N. S. & Istiyono, E. 2015. Studi Pelaksanaan
Pembelajaran Fisika Berbasis Higher Order Thinking (Hots) pada Kelas X di SMA
Negeri Kota Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional Fisika dan Pendidikan
Fisika (SNFPF) Ke-6 2015, 6 (1), 104-112. Dari https://www.neliti.com/publications/172905/studi-pelaksanaan-pembelajaran-fisika-berbasis-higher-order-thinking-hots-pada-k.
Siswoyo. & Sunaryo. 2017. High Order Thinking Skills: Analisis
Soal dan Implementasinya dalam Pembelajaran Fisika di Sekolah Menengah Atas. Jurnal
Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika, 3 (1), 11-20. Dari http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpppf/article/view/2498.
Yee, M. H., Othman, W., Yunos, M. D. J., Tee, T. K., Hassan, R., &
Mohamad, M. M. 2011. The Level of Marzano Higher Order Thinking Skills among
Technical Education Students. International Journal of Social Science and
Humanity, 1 (2), 121-125. Dari http://merr.utm.my/1589/.